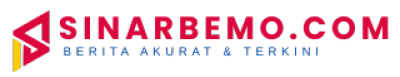Penulis adalah Adii Tiborius, Pemerhati masalah sosial Kepemudaan di daerah.
Pendahuluan
Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak penting dalam sejarah kebangkitan nasional Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda, generasi muda saat itu memproklamasikan tekad bersama: bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu — Indonesia. Sumpah ini bukan hanya sekedar deklarasi politik, namun juga merupakan manifestasi kesadaran hak asasi manusia (HAM): hak untuk diakui, dihormati, dan berpartisipasi sebagai bagian dari satu bangsa yang merdeka dan setara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks tanah Papua, peringatan Sumpah Pemuda memiliki makna yang lebih dalam. Papua adalah wilayah dengan kekayaan budaya, sumber daya alam, dan kearifan lokal yang luar biasa, namun juga menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan, ketimpangan pembangunan, dan dinamika politik yang kompleks. Oleh karena itu, memaknai Sumpah Pemuda dari perspektif HAM berarti menghidupkan kembali semangat persaudaraan, persatuan, dan kemanusiaan yang menghargai martabat setiap orang Papua tanpa diskriminasi.
1. Sumpah Pemuda dan Semangat Kemanusiaan Universal
Secara filosofis, Sumpah Pemuda merupakan revolusi nilai-nilai kemanusiaan universal. Para pemuda tahun 1928 mengikrarkan kesetaraan antar suku, agama, dan daerah, menolak penjajahan yang menindas martabat manusia, dan menciptakan kebebasan bersama dalam semangat kebangsaan.
Dengan demikian, Sumpah Pemuda tidak semata-mata menjadi simbol politik nasionalisme, tetapi juga bentuk pembelaan terhadap hak asasi manusia — hak untuk menentukan nasib sendiri dalam kebersamaan, hak untuk hidup damai, dan hak untuk diakui sebagai manusia yang membahayakan.
Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), yang menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama tanpa pembedaan ras, warna kulit, bahasa, agama, atau asal-usul sosial.
2. Kondisi HAM di Tanah Papua: Antara Harapan dan Tantangan
Persoalan hak asasi manusia di Papua telah menjadi perhatian nasional dan internasional. Sejarah panjang integrasi Papua ke dalam Indonesia, disertai dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, meninggalkan jejak perasaan ketidakadilan bagi sebagian masyarakat.
Beberapa isu HAM yang masih dihadapi masyarakat Papua antara lain:
Kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dengan pendatang.
Kasus pelanggaran HAM seperti kekerasan, terjadinya kebebasan berekspresi, dan penanganan konflik sosial yang tidak selalu berkeadilan.
Akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, yang berimplikasi pada pelanggaran hak-hak dasar warga.
Stigma dan diskriminasi rasial, baik secara struktural maupun kultural, terhadap orang asli Papua (OAP).
Dalam konteks ini, Sumpah Pemuda menjadi simbol moral untuk meneguhkan kembali nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat Papua yang selama ini sering berada di pinggiran pembangunan.
3. Menafsir Sumpah Pemuda sebagai Gerakan Hak Asasi
Sumpah Pemuda dapat dibaca sebagai gerakan awal pembebasan manusia dari pengkhianatan dan ketidakadilan. Ketika para pemuda tahun 1928 bersatu melawan kolonialisme, mereka sesungguhnya memperjuangkan hak dasar manusia untuk merdeka, hidup berkeyakinan, dan menentukan masa depannya sendiri.
Dalam konteks Papua, menafsir Sumpah Pemuda mempunyai arti:
1. Mengakui hak setiap orang Papua untuk diakui identitasnya sebagai bagian sah dari bangsa Indonesia tanpa pembedaan.
2. Menjamin kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berekspresi sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum.
3. Menghormati hak-hak adat dan hak atas tanah ulayat, sebagai bagian dari identitas sosial budaya masyarakat Papua.
4. Membangun keadilan sosial dan kesempatan yang setara, agar seluruh warga Papua dapat menikmati hasil pembangunan dan kemajuan bangsa.
Dengan demikian, Sumpah Pemuda menjadi landasan etis dan historis bagi perjuangan HAM di Papua — bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak akan bermakna tanpa adanya penghormatan terhadap martabat manusia.
4. Perspektif HAM dalam Pembangunan Papua
Hak asasi manusia harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan pembangunan di Papua. Pembangunan yang tidak berlandaskan nilai kemanusiaan hanya akan melahirkan ketimpangan baru.
Pendekatan pembangunan berbasis HAM mencakup:
Hak atas partisipasi : masyarakat Papua ikut berhak menentukan arah pembangunan yang menyentuh kehidupan mereka.
Hak atas identitas budaya : pembangunan harus menghormati bahasa, adat, dan struktur sosial masyarakat adat Papua.
Hak atas keadilan sosial : pendistribusian sumber daya alam harus dilakukan secara adil, dengan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Hak atas keamanan dan perdamaian : aparat negara dan masyarakat sipil harus bersama-sama memastikan tidak ada kekerasan atau pelanggaran dalam penegakan hukum dan pemerintahan.
Dengan demikian, nilai-nilai Sumpah Pemuda—persatuan, kebangsaan, dan solidaritas—dapat menjadi etika politik HAM di tanah Papua: membangun tanpa meniadakan, mempersatukan tanpa menindas, dan menghormati tanpa memaksakan.
5. Pemuda Papua sebagai Subjek Perjuangan HAM
Pemuda mempunyai posisi strategis dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Generasi muda Papua hari ini tidak hanya berperan sebagai penerus sejarah, tetapi juga sebagai penjaga moral bangsa dan agen transformasi sosial.
Pemuda Papua dapat memaknai Sumpah Pemuda dalam perspektif HAM melalui tiga peran utama:
1. Pendidikan dan Literasi HAM
Pemuda dapat menanamkan kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara, menolak kekerasan, dan menumbuhkan budaya dialog dalam penyelesaian konflik.
2. Advokasi dan Aksi Sosial
Pemuda perlu terlibat dalam organisasi kemanusiaan, gereja, LSM, atau media sosial untuk menyuarakan keadilan, lingkungan, dan kemanusiaan secara damai dan konstitusional.
3. Kepemimpinan Inklusif dan Moral
Pemimpin muda Papua harus tampil dengan wajah baru politik — politik yang humanis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa perubahan besar lahir dari keberanian anak muda untuk bersatu melampaui sekat-sekat identitas. Di Papua, nilai ini tetap relevan sebagai dasar perjuangan menegakkan HAM yang ditetapkan pada budaya kasih, keadilan, dan solidaritas sosial.
6. Membangun Papua yang Berkeadilan dan Bermartabat
Untuk membangkitkan semangat Sumpah Pemuda dalam konteks HAM di Papua, diperlukan langkah-langkah konkret:
Dialog kemanusiaan antara pemerintah dan masyarakat adat, sebagai sarana membangun kepercayaan dan rekonsiliasi.
Pendidikan HAM berbasis nilai lokal Papua, seperti onei (kasih), ewita (damai), dan wakai (keadilan).
Pemberdayaan masyarakat adat melalui kebijakan afirmatif dan program ekonomi berbasis komunitas.
Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, tanpa diskriminasi dan tanpa kekerasan.
Dengan langkah-langkah tersebut, semangat Sumpah Pemuda dapat menjadi roh kemanusiaan bagi pembangunan Papua yang damai dan mengakui.
7. Kesimpulan
Memaknai Hari Sumpah Pemuda dalam perspektif hak asasi manusia di tanah Papua berarti mengembalikan makna kemerdekaan kepada manusia — bahwa setiap orang Papua memiliki hak yang sama untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa.
Sumpah Pemuda bukan hanya milik masa lalu, melainkan kompas moral masa depan: mengarahkan bangsa Indonesia, termasuk Papua, untuk menegakkan keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Bagi generasi muda Papua, Sumpah Pemuda adalah panggilan untuk bersatu, berjuang tanpa kekerasan, dan memperjuangkan kemanusiaan melalui jalan damai. Dengan semangat itu, Papua akan menjadi contoh bahwa persatuan sejati hanya dapat tumbuh dari rasa hormat terhadap hak asasi manusia.
Daftar Pustaka
Komnas HAM RI. Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Jakarta: Komnas HAM, 2022.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Nilai-Nilai Sumpah Pemuda dan Relevansinya di Era Modern. Jakarta: BPIP, 2021.
Rumansara, Yance. HAM dan Politik Identitas di Papua. Jayapura: Cenderawasih Press, 2019.
UNDP Indonesia. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Pembangunan di Papua. Jakarta: UNDP, 2021.
Hidayat, Syarif. Pendidikan HAM dan Demokrasi di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2015.