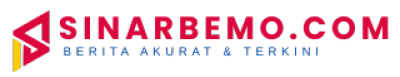Oleh: MP
Mahasiswa Papua di Jawa
Tanah Papua sejak lama dikenal sebagai wilayah yang kaya secara alamiah namun rentan secara sosial dan politik. Dalam perjalanannya, Papua mengalami banyak fase transformasi, salah satunya adalah pemekaran wilayah yang kini diwujudkan dalam bentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Meski pemerintah pusat menyebut DOB sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan publik, kenyataan di lapangan justru memunculkan berbagai pertanyaan dan kecurigaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai anak muda Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar tanah kelahiran, saya menulis ini sebagai bentuk keresahan dan kesadaran kolektif. Saya menyaksikan bahwa Papua yang dulu dikenal dengan kedamaian, kini berubah drastis. Konflik, kemiskinan, marginalisasi, dan eksploitasi menjadi bagian dari narasi harian yang tidak bisa lagi diabaikan.
Mitos Pemerataan Melalui DOB
Secara teori, DOB bertujuan mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun praktiknya justru menunjukkan bahwa DOB lebih banyak dimanfaatkan sebagai celah bagi kepentingan elit politik dan ekonomi. Alih-alih memberdayakan Orang Asli Papua (OAP), DOB membuka ruang eksploitasi kekayaan alam secara lebih masif dan terstruktur.
Salah satu indikasi yang mencolok adalah meningkatnya jumlah perusahaan, baik domestik maupun asing, yang masuk dan menguasai sektor-sektor strategis di Papua. Berdasarkan data dari RRI.co.id, di wilayah Papua Barat Daya tercatat sekitar 39.721 perusahaan, namun hanya 2.670 yang memiliki data lengkap dan terverifikasi. Di sisi lain, Tabloid Papua Baru mencatat sekitar 263 perusahaan penanaman modal dalam negeri dan asing beroperasi di Papua, dan data BPS menunjukkan 29 perusahaan manufaktur skala besar serta 10 perusahaan food estate di Merauke menurut Tempo.co.
Semua ini membuktikan bahwa Papua menjadi ladang eksplorasi dan eksploitasi, bukan ladang pemberdayaan OAP.
Eksploitasi dan Ketidakadilan Sosial
Kekayaan alam Papua, seperti tambang emas di Mimika yang dikuasai oleh PT Freeport Indonesia, hanyalah satu dari sekian banyak sumber daya yang terus digali. Ironisnya, keberadaan perusahaan-perusahaan ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, OAP kian terpinggirkan, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya.
Mama-mama Papua adalah contoh paling nyata. Mereka masih harus berjualan di pinggir jalan di bawah terik matahari dan guyuran hujan, terpapar polusi kendaraan, demi menyambung hidup. Tempat berdagang yang layak memang ada, namun seringkali telah dikuasai pedagang non-OAP. Ini bukan hanya soal fasilitas, melainkan ketimpangan akses dan kebijakan.
Di sektor ketenagakerjaan pun, OAP masih dianggap sebagai pelengkap. Meski banyak anak muda Papua telah menempuh pendidikan tinggi dan memiliki kapasitas, namun peluang kerja—terutama di sektor formal—lebih sering diberikan kepada non-OAP. Pemerintah dan perusahaan cenderung mengabaikan prinsip keberpihakan dan keadilan sosial.
Perda yang Hanya Jadi Ilusi
Di atas kertas, Papua memiliki instrumen hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) yang seharusnya melindungi hak ulayat, budaya, dan kelestarian hutan. Namun, banyak dari regulasi ini tidak berjalan maksimal karena harus menunggu harmonisasi dari pusat, bahkan terkadang harus menunggu “lampu hijau” dari Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, semua ini menjadi semacam ilusi hukum—hadir secara formal, namun tidak berdampak substantif.
DOB dalam konteks ini tak ubahnya seperti permen manis dari pemerintah pusat: enak di awal, tapi cepat habis dan meninggalkan rasa pahit. Harapan-harapan seperti peningkatan kualitas hidup, pemerataan ekonomi, dan partisipasi demokratis bagi OAP, hingga kini masih jauh panggang dari api.
Tanya yang Harus Dijawab Pemerintah
Lalu, apakah dengan adanya pemekaran ini OAP benar-benar merasakan manfaat pembangunan? Apakah mereka memiliki ruang untuk berekspresi, berdemokrasi, dan menentukan nasib sendiri? Atau justru mereka hanya menjadi korban sistematis dari kebijakan negara?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh pejabat di Jakarta, tetapi oleh realitas sehari-hari yang dihadapi masyarakat Papua sendiri.
Penutup: Jaga Tanah Kita
Pada akhirnya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Papua bukan tanah kosong. Ini adalah tanah yang diwariskan oleh leluhur dengan keringat, air mata, dan darah. Tanah ini adalah identitas, harga diri, dan rumah bagi OAP. Maka, mari kita jaga.
Pemekaran wilayah seharusnya tidak menjadikan Papua sebagai tumbal bagi kepentingan ekonomi-politik segelintir elite. Kita perlu menagih kembali janji-janji pembangunan yang berkeadilan. Kita perlu bersuara.
Tanah Papua hari ini tidak sedang baik-baik saja. Mari buka mata, mari bersuara.
“DOB hanyalah tumbal.”